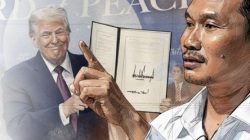DI TENGAH arus deras politik rekonsiliasi pasca-Pemilu 2024, muncul suara-suara sumbang dari para intelektual dan aktivis publik yang menolak jalan damai atas satu isu krusial: dugaan ketidakabsahan ijazah Presiden Joko Widodo. Roy Suryo, pakar telematika dan mantan Menpora; Rismon Sianipar, peneliti independen yang intens dalam riset otentikasi dokumen; serta dr. Tifa, aktivis medis yang juga vokal dalam advokasi keadilan konstitusional, menyatakan penolakan tegas terhadap penyelesaian kompromistis atas perkara ini.
Pertanyaannya: Mengapa mereka menolak berdamai? Apakah ini sekadar sikap politis, atau ada soal yang lebih mendasar: tentang hak publik atas kejujuran, keterbukaan, dan integritas konstitusional?
Hilangnya Nalar Publik dan Transparansi Negara
Dalam demokrasi modern, integritas pemimpin bukan hanya soal elektabilitas, tetapi soal kredibilitas epistemik—sebuah istilah dari filsuf Miranda Fricker (2007), yang mengacu pada hak seseorang untuk dipercaya berdasarkan basis kebenaran. Jika pemimpin tidak dapat menunjukkan bukti otentik atas identitas akademiknya, maka hak rakyat untuk percaya juga dilucuti.
Hingga hari ini, ijazah asli Presiden Jokowi dari Fakultas Kehutanan UGM tidak pernah ditampilkan ke publik, melainkan hanya berupa fotokopi yang ditandatangani rektor dan dibela oleh institusi-institusi formal. Padahal, dalam perkara kenegaraan, otentikasi tidak boleh hanya berdasarkan “kepercayaan institusional”, tapi harus berbasis verifikasi empiris.
Penelusuran Rismon Sianipar dan beberapa pakar forensik dokumen menunjukkan adanya kejanggalan kronologis. Misalnya, font Times New Roman yang digunakan dalam ijazah diduga belum terinstal secara luas di sistem komputer Indonesia pada tahun 1980-an. Laporan dari Microsoft sendiri menyebutkan bahwa font ini baru menjadi standar sejak Microsoft Windows 3.1 dirilis pada tahun 1992.
Dalam dunia akademik dan hukum, ini menjadi indikator red flags, —istilah dalam literatur forensik dokumen (Watt & Brown, Forensic Document Examination, 2010)—yang menunjukkan potensi rekayasa atau pemalsuan. Penjelasan kampus dan LLDIKTI tidak menjawab secara tuntas, justru menambah keraguan dengan narasi yang berubah-ubah.
Penolakan Damai: Etika Melawan Impunitas
Roy Suryo menyebut bahwa “bukan soal menyerang pribadi Jokowi, tetapi soal mendidik bangsa agar tidak permisif terhadap pemalsuan.” Bagi dr. Tifa, ini bukan sekadar ijazah, tetapi ujian atas integritas sistem demokrasi yang semakin mengandalkan simbol daripada substansi.
Teori impunitas struktural yang diajukan oleh Boaventura de Sousa Santos menyatakan bahwa ketika pelanggaran dilakukan oleh mereka yang memiliki kuasa, dan negara gagal mengadilinya, maka impunitas menjadi norma baru. Ini yang ditolak mentah-mentah oleh ketiga tokoh tersebut.
Pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan bahwa calon presiden harus memiliki ijazah SMA atau sederajat. Jika ada indikasi pemalsuan data, maka Pasal 263 dan 264 KUHP tentang pemalsuan dokumen dapat berlaku. Namun, perkaranya bukan hanya soal pidana, melainkan etika konstitusional: apakah bangsa ini akan membiarkan sejarahnya dibangun atas fondasi keraguan?
Salah satu narasi pembelaan yang sering dikemukakan oleh kelompok pendukung Presiden Jokowi dalam menanggapi polemik ijazah adalah bahwa seorang presiden tidak dapat digugat secara hukum karena memiliki kekuasaan eksekutif. Namun, pandangan ini mendapat kritik tajam dari kalangan ahli hukum pidana.
Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, pakar hukum pidana dan mantan anggota Wantimpres, dalam beberapa kesempatan menegaskan bahwa “penguasa umum” dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tidak otomatis melekat pada pejabat publik setelah purna jabatan. Dengan kata lain, ketika seseorang sudah tidak lagi menjabat atau telah melepaskan kekuasaan administratif, maka ia bisa menjadi subjek penyelidikan hukum secara umum, tanpa kekebalan khusus.
Dalam konteks Presiden Jokowi, jika setelah masa jabatan selesai pada 2024-2025 tidak ada klarifikasi resmi atau pembuktian otentik atas keaslian ijazahnya, maka secara teoritis, proses hukum tetap bisa berlangsung. Ini sejalan dengan doktrin dalam hukum pidana positif Indonesia bahwa “tidak ada seorang pun yang kebal terhadap proses hukum apabila terdapat bukti permulaan yang cukup” (Asas equality before the law).
Dr. Mudzakkir, pakar pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII), bahkan menyebut bahwa kasus dugaan pemalsuan dokumen akademik yang tidak diselesaikan pada masa jabatan aktif berpotensi menjadi warisan kriminal terbuka. Hal ini berbahaya bagi legitimasi hukum negara, sebab akan menciptakan preseden bahwa jabatan publik bisa menjadi tameng bagi dugaan pelanggaran pidana.
Isu ijazah Jokowi seolah direduksi menjadi “hoaks” oleh elite politik, padahal ia menyangkut legitimasi sejarah dan moral negara. Menyerukan damai tanpa menyelesaikan substansi adalah rekonsiliasi semu, seperti yang dikritik oleh Johan Galtung dalam konsep “negative peace” – damai yang hampa tanpa keadilan.
Roy, Rismon, dan dr. Tifa memilih jalan sepi, jalan yang menuntut transparansi dan kejujuran. Mereka tidak sedang membenci seseorang, tapi sedang mencintai republik ini dengan cara paling jujur: menolak berdamai atas kebohongan.
Dalam demokrasi yang sehat, kebenaran tidak bisa dikompromikan, apalagi disingkirkan demi stabilitas politik. Kasus ijazah Jokowi bukan soal legal-formal semata, tetapi soal etika kolektif kita sebagai bangsa. Jika kecurigaan publik dianggap angin lalu, maka negara ini sedang melatih rakyatnya untuk takut bertanya. Dan ketika rakyat takut bertanya, maka demokrasi telah mati, tanpa harus dibunuh. (*)
Selwa Kumar;
Penulis adalah Penggiat Peradaban.