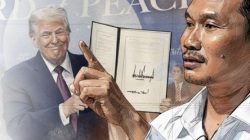SEBELUM bangsa ini mengenal istilah “pendidikan nasional”, sistem pendidikan telah lebih dahulu hidup dan berkembang melalui institusi tradisional Islam seperti pesantren. Pesantren bukan hanya tempat menimba ilmu agama, tetapi juga membentuk watak dan karakter sosial masyarakat Muslim. Namun, pesantren bersifat terbatas dan tidak menjangkau kebutuhan masyarakat luas yang mulai terdesak oleh modernitas dan kolonialisme.
Situasi berubah dengan diberlakukannya politik etis oleh pemerintah kolonial Belanda pada awal abad ke-20. Kebijakan ini muncul sebagai bentuk “balas budi” terhadap bangsa Indonesia setelah eksploitasi panjang lewat tanam paksa dan kerja rodi. Politik etis melahirkan tiga agenda utama: irigasi, emigrasi, dan edukasi. Dari ketiganya, edukasi menjadi faktor paling menentukan munculnya kesadaran nasional.
Sekolah-sekolah mulai dibuka untuk bumiputra, meskipun tetap bersifat diskriminatif dan cenderung mendidik elite lokal agar menjadi perpanjangan tangan kolonial. Namun, inisiatif ini secara tak langsung menumbuhkan semangat baru untuk membangun pendidikan sendiri yang merdeka, membebaskan, dan sesuai dengan nilai bangsa.
Dalam konteks inilah, dua tokoh besar muncul sebagai arsitek pendidikan kebangsaan: KH Ahmad Dahlan melalui Muhammadiyah, dan Ki Hajar Dewantara melalui Taman Siswa. Keduanya bukan hanya mendirikan sekolah, tetapi juga membangun sistem pemikiran dan aksi yang menjadikan pendidikan sebagai bagian integral dari perjuangan nasional.
Muhammadiyah
KH Ahmad Dahlan lahir di Kauman, Yogyakarta, dari keluarga ulama terpandang. Ia memperoleh pendidikan agama secara tradisional, kemudian melanjutkan studi ke Makkah, di mana ia bersentuhan dengan gagasan pembaruan Islam dari tokoh-tokoh seperti Muhammad Abduh dan Rashid Rida¹. Perjumpaan ini menumbuhkan kesadaran bahwa umat Islam harus kembali pada Alquran dan Sunnah, serta menyesuaikan ajaran agama dengan tantangan zaman.
Dahlan sempat aktif dalam Budi Utomo, organisasi kebangsaan awal yang berbasis identitas Jawa. Namun, ia segera menyadari keterbatasan Budi Utomo yang cenderung elitis dan tidak menyentuh akar masalah umat Islam, khususnya dalam bidang pendidikan. Maka pada tahun 1912, ia mendirikan Muhammadiyah, sebuah gerakan Islam modern yang menjadikan pendidikan sebagai alat utama perubahan sosial².
Karakteristik Pendidikan Muhammadiyah: Sebuah Sintesis Progresif
Pendidikan Muhammadiyah menawarkan sintesis progresif antara ajaran Islam dan metode pendidikan modern Barat. Jika pendidikan kolonial dan misionaris Kristen mengusung nilai-nilai sekular dan dogma agama lain, maka Muhammadiyah hadir sebagai alternatif Islam yang rasional, terbuka, dan berbasis etika serta ilmu pengetahuan.
Sekolah-sekolah Muhammadiyah menggunakan kurikulum yang menggabungkan pelajaran agama dengan ilmu umum. Guru-guru dilatih secara sistematis, dan manajemen sekolah disusun dengan prinsip efisiensi serta tanggung jawab sosial. Pendidikan Muhammadiyah juga menekankan kedisiplinan, kebersihan, dan keterbukaan terhadap sains. Dalam hal ini, Ahmad Dahlan mereformasi cara berpikir umat—bahwa Islam dan kemajuan tidaklah bertentangan.
Kiprah dalam Pendidikan Nasional: Islam sebagai Kekuatan Pembebasan
Kontribusi Muhammadiyah terhadap pendidikan nasional tidak hanya dapat diukur dari jumlah sekolah yang didirikan dan penyebarannya di seluruh wilayah Indonesia, namun jauh lebih penting adalah warisan model pendidikan Islam yang modern, non-sektarian, dan transformatif. Dalam konteks kolonial, Muhammadiyah telah menjadi pelopor pendidikan berbasis rakyat yang tidak bergantung pada bantuan pemerintah kolonial.
Lebih dari itu, Muhammadiyah membentuk kader-kader bangsa yang memiliki semangat keislaman sekaligus keilmuan. Mereka adalah pendidik, dokter, jurnalis, dan politisi yang berkiprah dalam perjuangan kemerdekaan. Pendidikan Muhammadiyah, dengan demikian, menjadi infrastruktur sosial bagi munculnya kelas menengah Muslim yang sadar politik dan progresif.
Taman Siswa
Ki Hajar Dewantara, yang lahir sebagai Suwardi Suryaningrat, berasal dari keluarga bangsawan Yogyakarta dan mengenyam pendidikan Barat sejak kecil. Namun, pengalaman itu justru menumbuhkan kritik tajam dalam dirinya terhadap sistem pendidikan kolonial yang diskriminatif dan menindas. Setelah diasingkan ke Belanda akibat tulisan “Seandainya Aku Seorang Belanda”, ia mendalami pendidikan dan filsafat humanisme, termasuk pemikiran Theosofi yang kelak memengaruhi pendekatannya dalam mendidik.
Pada tahun 1922, ia mendirikan Taman Siswa di Yogyakarta sebagai bentuk perlawanan terhadap hegemoni pendidikan kolonial. Ia mengembangkan sistem pendidikan alternatif yang membebaskan rakyat kecil dari ketergantungan pada sekolah pemerintah.
Karakteristik Pendidikan Taman Siswa: Tradisi, Kebatinan, dan Kemerdekaan Batin
Taman Siswa dibangun di atas falsafah kemerdekaan batin, yaitu membentuk manusia merdeka secara jiwa sebelum menuntut kemerdekaan secara politik. Pendidikan tidak boleh menindas, tetapi harus mengembangkan kepribadian, kreativitas, dan kepekaan sosial peserta didik. Karakteristik utama Taman Siswa mencerminkan sintesis antara nilai-nilai pendidikan Barat dan spiritualitas Timur, terutama kebatinan Jawa dan ajaran theosofi.
Ki Hajar menolak pendidikan formal yang menekankan otoritas guru dan hafalan. Sebagai gantinya, ia menekankan pendekatan kontekstual, hubungan kekeluargaan dalam proses belajar, dan pembentukan karakter melalui seni, budaya, dan kehidupan bermasyarakat.
Kemerdekaan, Kodrat Alam, Kebudayaan, Kebangsaan dan Kemanusiaan
Dengan dasar tersebut, pendidikan di Taman Siswa tidak hanya bertujuan mencetak pekerja atau pejabat, tetapi menciptakan manusia merdeka yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga bangsa dan dunia.
Taman Siswa tidak mendirikan sekolah sebanyak Muhammadiyah, namun pengaruhnya terhadap filosofi pendidikan naaional sangat kuat. Konsep pendidikan Ki Hajar seperti “Ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani” diadopsi menjadi asas pendidikan nasional. Meski hal ini tudak bisa dilepaskan dari faktor politis.
Ki Hajar menjadi Menteri Pendidikan pertama RI, dan pemikirannya tentang pendidikan berbasis kebudayaan juga menjadi rujukan UU Sistem Pendidikan Nasional. Ia membuktikan bahwa pendidikan bukan hanya soal kurikulum atau gedung, tetapi soal visiun kebudayaan dan pembebasan manusia secara utuh⁷.
Kesimpulan
Muhammadiyah dan Taman Siswa adalah dua pilar penting dalam sejarah pendidikan Indonesia. Keduanya menawarkan model pendidikan yang bukan hanya berbeda dari kolonialisme, tetapi juga mengakar pada kebutuhan dan nilai bangsa sendiri. Lalu siapa layak disebut pelopor pendidikan nasional? Keduanya—dengan pendekatan masing-masing berperan krusial:
KH Ahmad Dahlan melalui Muhammadiyah adalah pelopor secara struktural dan sosial, aspek kelembagaan dan modernisasi pendidikan, memberi kontribusi yang sangat besar dalam memperluas akses pendidikan dan membentuk manusia religius, rasional dan nasionalis.
Ki Hajar Dewantara adalah pelopor secara ideologis dan filosofis. Visinya pemdidikan adalah alat perjuangan kebudayaan, bukan hanya pencapaian akademik. Ki Hajar meletakkan dasar-dasar pembebasan manusia Indonesia secara lahir dan batin, dan menjadikan pendidikan sebagai kekuatan revolusioner yang lembut namun radikal.
Dan faktanya secara politis Ki Hajar Dewantara yang ditetapkan sebagai Tokoh Pelopor Pendidikan Nasional. Ia yang dianggap menyusun asas, filsafat, dan sistem pendidikan nasional yang diakui dan diadopsi oleh negara. (*)
Nazaruddin;
Penulis adalah Wakil Ketua Umum DPP Partai Ummat.